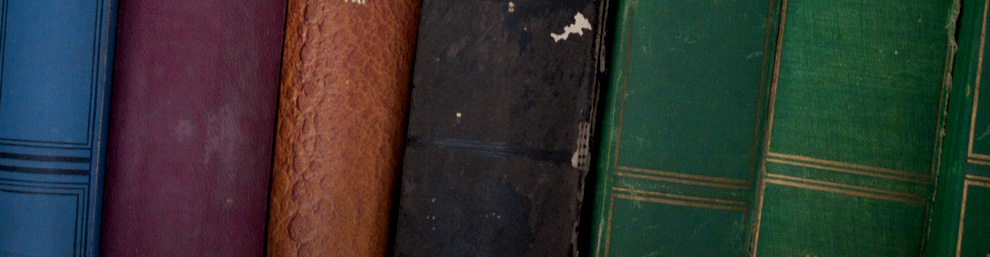“Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan dimuka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS Al Kahfi [18]:45-46)
Pertanyaan itu begitu memukaunya. Hamba itu terdiam sebentar tak mampu untuk menjawabnya. Jarang dalam suasana kehidupan seperti saat sekarang ini, pertanyaan itu muncul. Terlebih dari seseorang yang dikasihi dan telah bersama mengarungi kehidupan rumah tangga lebih dari sewindu. Sang penanya terlihat gundah dengan lingkungan tempat ia berpijak. Diantara teman-temannya, ia merasakan bahwa ‘Kebendaan’ dan ‘Pencapaian-pencapaian pribadi itu’ selalu menjadi topik pembicaraan yang tak habis-habisnya. Untuk itu ia bertanya,
“Bagaimana bersikap zuhud dalam lingkungan seperti ini? Disatu sisi kita harus selalu membina silaturrahim, sementara Rasulullah Saw mengajurkan kita untuk bersikap zuhud? Apakah kita harus menutup diri dan menghindar dari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada kecintaan pada dunia ini? Bukankah sisi ‘modern’ dari sebuah kehidupan itu akan selalu bertumbukan dengan sisi ‘keimanan’ yang ada di hati kita? Bagaimana kita harus bersikap?
‘Zuhud tidaklah diartikan dengan kemiskinan, kekurangan dan menutup diri dari segala pergaulan yang menjerumuskan. Zuhud lebih dimaknai sebagai ‘kesederhanaan sebagai pilihan hidup’. Jika memang pilihan itu terpampang dihadapan kita. Ketika Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kepada seorang hamba untuk hidup dalam kelapangan, justru simbol-simbol kemewahan itu tidak pernah dipertontonkannya kepada siapapun. Ia memilih untuk tetap hidup dalam kesederhanaan dan apa adanya.
Hamba itu teringat akan sebuah kisah dari seorang khalifah yang agung dimasa Islam, Umar Ibn Khatab ra. Seorang sahabat Nabi Saw yang zuhud. Di awal pemerintahannya, dalam suatu riwayat disampaikan bahwa ia pernah berdoa, “Ya Allah, jadikan dunia ini dalam genggamanku, tapi tidak dihatiku.” Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Di masa pemerintahannya 2/3 dunia ini berada dalam genggamannya. Kekuasaan Romawi dan Persia sebagai dua poros kekuatan utama dunia saat itu dapat dikuasainya dengan sangat baik.
Ketika Jerusalem telah dikuasai oleh pasukan Islam, Khalifah Umar ra datang sendiri yang hanya diikuti oleh seorang pengawalnya. Ketika itu ia disambut oleh panglima pasukan Islam, Abu Ubbaidah bin Jarrah ra dan pembesar-pembesar Yerusalem. Khalifah Umar hanya memakai pakaian yang sangat sederhana sehingga ia diperingatkan oleh Abu Ubaidah untuk mengganti pakaiannya. Khalifah Umar marah dan berkata, “Wahai Abu Ubaidah, dahulu kita adalah manusia yang hina. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Apakah pantas bagi kita untuk menyombongkan diri agar manusia lain memandang kita sebagai orang yang mulia?
Khalifah Umar benar, kemuliaan seseorang bukan terletak pada bagusnya pakaian, mahalnya kendaraan yang ia pergunakan dan simbol-simbol kemewahan lainnya yang ia miliki. Tapi lebih kepada pancaran wajah yang meneduhkan yang dapat membawa kedamaian bagi siapapun yang berhubungan dengannya dan akhlak mulia yang selalu menghiasi perangainya dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain mendapat manfaat yang banyak dari keberadaannya.
Seorang sahabat Rasulullah Saw pernah bertanya kepada Nabi, “Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengerjakannya maka aku akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintai manusia lain.” Nabi menjawab, “Janganlah kamu rakus terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu dan janganlah kamu rakus terhadap hak orang lain, pasti orang lain mencintaimu.” (HR Ibnu Majah)
Allah Azza wa Jalla memberi perumpamaan dalam ayat-Nya yang penuh hikmah yang dikutip pada awal tulisan ini bahwa kehidupan dunia ini bagai air hujan. Ini memberi hikmah kepada kita bahwa air hujan yang turun dengan cukup (tidak berlebihan dan tidak pula sedikit) akan membawa keberkahan bagi apapun yang menimpanya. Ia akan menjadikan tanah menjadi subur, hingga tanaman dapat menghasilkan dengan baik. Hal ini akan memuaskan manusia yang secara pasti menggantungkan sumber hidupnya pada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Ketika musim hujan telah berlalu berganti dengan musim kering, tumbuh-tumbuhan itu akan mengering dan tak dapat diselamatkan lagi. Ia akan punah tak berbekas dan dilupakan oleh manusia yang telah memuji sebelumnya.
Kalau kita coba merenung lebih dalam hikmah pada ayat diatas, Allah Azza wa Jalla memberi pengajaran kepada kita bahwa ‘air hujan’ bagaikan ‘rezeki’ yang ia berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan rezeki yang lebih pada seseorang, maka ia akan tampak begitu memukau bagi orang-orang yang melihatnya. Tapi ketika Allah mempersempit rezekinya, maka orang-orang akan cenderung untuk melupakannya. Bahkan yang sering terjadi adalah orang-orang akan cenderung mencelanya seolah kesempitan rezeki itu adalah karena ‘kesalahannya’ dalam mengusahakannya.
Harta dan anak-anak merupakan bagian dari rezeki Allah yang tidak bergantung pada usaha atau amal shaleh seseorang dalam memperolehnya. Begitu banyak hamba-hamba Allah yang shaleh tapi memperoleh kesempitan rezeki sehingga harus selalu tertatih-tatih dalam menjalani hidupnya. Dalam sisi yang lain, begitu banyak orang-orang kafir yang rezekinya melimpah ruah hingga keluar pernyataannya yang amat sombong, “Bukan aku yang bekerja, tapi uang yang berkerja untukku!” Allah mencela orang-orang yang berpendirian seperti ini dalam QS Al Fajr [89] 15-20.
Rezeki adalah hak Allah dalam menentukan. Kepada siapa Allah akan berikan dan seberapa banyak yang akan Allah berikan. Bukan karena keta’atan dan bukan pula karena kekufuran. Adalah kurang pantas bagi kita untuk membahas kenapa rezeki si A lebih daripada si B. Kenapa si A memperolehnya sedang si B tidak? Kenapa kita harus selalu mempersoalkannya? Bukankah dengan mempertanyakannya, berarti kita mempertanyakan takdir (baca: Qadha & Qadar) yang Allah telah tetapkan puluhan ribu tahun sebelum kehadiran manusia di muka bumi ini? Hal ini adalah sebuah ke-naif-an buat kita untuk mengetahui rahasia-Nya.
Yang seharusnya terjadi, menurut ayat diatas adalah bagaimana cara kita mengisi kehidupan ini dengan amal shaleh yang banyak. Sadar akan peran kita di masyarakat adalah awal bagi kita untuk melakukan amal shaleh. Seorang pekerja akan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran. Bukankah ini sebuah amal shaleh? Seorang pengusaha akan selalu memikirkan nasib pekerjanya agar dapat terpenuhi segala kebutuhan mereka dan menginfakkan sebahagian kelebihan keuntungan yang ia peroleh untuk membantu beasiswa anak-anak yatim dan jaminan kesehatan orang-orang miskin. Bukankah ini sebuah amal shaleh? Demikian juga seorang suami yang selalu ingin membahagiakan pasangan hidupnya dan anak-anaknya dengan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka dan selalu bersikap lemah lembut serta penuh perhatian. Bukankah ini adalah amal shaleh? Seorang istri yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa harus bersikap kasar kepada mereka. Bukankah ini juga amal shaleh?
Zuhud tidaklah bertumbukan dengan kehidupan modern yang lebih menonjolkan ‘kebendaan’. Justru sikap zuhud yang ditunjukkan oleh seorang hamba akan menjadi nilai diri yang amat menonjol yang dapat membawa kedamaian dalam pergaulan. Bukankah sikap hidup menonjolkan simbol-simbol kekayaan menyebabkan persaingan yang tiada habis-habisnya karena ingin terlihat lebih diantara yang lain? Sikap zuhud- lah yang dapat meredam semua itu.
Rasulullah Saw bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah ra, “Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian dan celakalah hamba perut! Jika telah terpenuhi, ia bahagia dan apabila tidak terpenuhi maka ia akan merasa sedih.” (HR Bukhari)
Yang fakir kepada ampunan Rabb-nya Yang Maha Berkuasa,M. Fachri